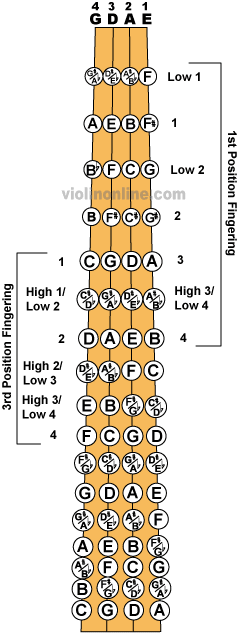Sekali air besar, sekali tepian berubah (sakali aia gadang sakali tapian barubah), demikian pepatah lama yang selalu dibaca-bacakan ketika terjadi perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan singkat ke Malioboro Yogyakarta September 2023 meninggalkan kesan yang sama. Becak yang dikayuh oleh manusia sekarang dikayuh oleh mesin. Pengendara cukup menekan starter, masin hiduik roda babeleang (mesin hidup roda berputar). Becak motor telah berangsur-angsur menggantikan becak kayuh (gowes). Begitulah kehidupan ini ketika ada yang lebih cepat lebih praktis, suatu tradisi berangsur-angsur berubah apakah lambat atau drastis. Tak ada lagi yang kenal lampu strongkeng (baca Stormking) karena sudah ada lampu neon dan sekarang malah pakai lampu LED. Kembali ke pepatah di atas, bahwa air besar itu hanyalah merubah letak tapian. Yang tapian itu tetaplah tapian. Pada dasarnya manusia butuh cahaya di malam hari, semuanya adalah sumber cahaya untuk manusia beraktivitas di dalam hari, mulai dari nyala api unggun, suluh, lampu dama, petromax, lampu neon/TL sampai sekarang ke lampu LED.
Ketika semuanya sudah serba modern, di kawasan wisata, adakalanya orang butuh suasana masa lalu, tidak masalah, bagusnya di kawasan wisata saja, tarif untuk penggunaan jasa "seperti masa lalu" itu bayarnya lebih mahal daripada jasa yang ada di zaman modern. Kalau tidak, maka jasa becak kayuh itu pastilah akan punah ditelan zaman, kita hanya rindu, tapi siapa pelaku dari objek kerinduan itu?. Kita ingin kembali ke masa lalu, sebuah keinginan yang melawan arus zaman, tentu ada konsekuensinya, bayarlah lebih mahal karena untuk dinikmati sekali-sekali saja. Meskipun sarana transportasi di Jepang sudah sedemikian canggih, kita masih bisa menikmati suguhan tradisional becak manusia (rickshaw) atau jinrikisha (人力車), becak manusia yang dulu lazim terjadi di Asia. Tapi yaaa "sore wa takai desu, nee" (itu mahal lho..) karena itu jasa untuk kawasan wisata. Becak manusia ini dulunya ada di jaman penjajahan Belanda, tapi entahlah kalau di Ranah Minang, bisa saja dulu ada.. Tapi yang saya saksikan semasa kanak-kanak adalah hanyalah bendi saja. Kereta yang ditarik orang itu tidaklah lagi dijumpai tahun 1980-an. Bendi ini akhirnya tidaklah laris lagi digantikan oleh bemo, angkutan mini (oplet, carry) dan cigak baruak (angkutan pedesaan, angdes) di kampung-kampung. Makanya kita dengar dendang tukang Rabab Pesisir Hasan Basri mengatakan:
Apa ka dayo si pisang lidi (apalah daya si pisang lidi)
Batang lansek alah rabah pulo (batang langsat sudah rebah pula)
Apo ka dayo si kusia bendi (apa lah daya si kusir bendi)
Oto ketek manambang pulo (mobil mini menambang [ikutan narik] pula)
Asben dan Melati, duet penyanyi Minang legendaris pernah membawakan lagu Ratok Karisiak (Ratap Kerisik). Karisiak (kerisik) adalah daun pisang yang sudah mengering. Liriknya bagus sekali, dahulu daun pisang, ini barabuik urang maambiak (berebutan orang mengambil), ditanai seperti melipat kain, dan bahkan dijunjung ke pasar supaya tidak rusak daunnya. Bukti penghargaan kepada daun pisang itu pertama, disegerakan, kedua diperlakukan baik-baik dan ketiga dijunjung (diletakkan di posisi) tertinggi ketika masuk ke keramaian (pasar). Sekarang zaman telah berganti, plastik sudah merajalela, praktis dan murah. Akibatnya daun pisang tidak pendapatkan prioritas lagi, hingga sampai jadi karisiak (kerisik) yang tergantung di batang pisang. Namun, pada akhir lagu duet legendaris ini kembali berharap kiranya nanti daun pisang naik pamor lagi. Ya, saya menikmati makan dengan daun pisang di pondok setelah menemani nenek ke sawah dulunya tahun 1984 di kampung. Lalu kembali menikmati makan dengan daun pisang ini di rumah makan India di dekat University of Malaya, Kuala Lumpur tahun 2006. Tentu saja tarifnya mahal. Kalaulah makan dengan daun pisang dengan pemandangan sawah ada restorannya, tentu saja tarifnya beda dengan tarif rumah makan di kawasan ibu kota yang sesama rumah makan padang, saling banting harga sampai tahun 2023 ada rumah makan Padang (Minang) harga Rp.10.000/bungkus. Perang tarif yang mengerikan, yang menjadikan rumah makan padang lebih murah dari warteg yang dulu dianggap kelasnya oleh 'kalangan tertentu' di bawah RM Padang. Tentu saja anggapan itu tidak sepenuhnya benar, masalah rasa itu tidak bisa dibandingkan. Ya begitulah.. bukan warteg yang 'melibas' RM Padang karena beda segmen pasar, tapi awak samo awak (kita sama kita). Andaikan kita masih memakai tradisi raso-raso seperti dulunya, tentu ini dapat dicegah.
Sekarang, artificial intelligence (AI) sudah merambah peradaban, ini adalah aia gadang tipe galodo (air bah datang mendadak, menghanyutkan apa saja yang dilewatinya tanpa ampun) tentunya kita bersiap-siap menyaksikan seperti apa bentuk tapian-tapian (tepian) di masa mendatang.